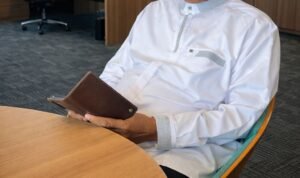BUDAYA PERJUMPAAN:
Antarumat Lintas Agama dan Dampaknya terhadap Harmoni Bangsa
Oleh: Duski Samad
Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat
Budaya perjumpaan dalam interaksi sosial adalah kebiasaan, nilai, dan praktik yang mendorong individu atau kelompok dari latar belakang berbeda — terutama dalam hal agama, budaya, atau identitas sosial lainnya — untuk bertemu, berinteraksi, berdialog, dan membangun hubungan secara terbuka dan setara.
Ciri-ciri Budaya Perjumpaan adalah
terbuka terhadap perbedaan.
Menghargai keberagaman dan tidak menutup diri terhadap kelompok lain. Berbasis kesalingan (reciprocity).
Tidak didominasi satu pihak, tapi terjadi pertukaran pemikiran, pengalaman, dan empati. Dilandasi niat baik (husnuzhan)
Ada prasangka baik bahwa pihak lain layak dihormati dan didengar.
Terjadi dalam ruang nyata maupun simbolik. Bisa berbentuk forum dialog, kerja sama sosial lintas kelompok, atau interaksi harian yang saling membangun. Menghasilkan rasa saling percaya dan solidaritas
Bukan sekadar komunikasi, tapi menumbuhkan rasa “kita” dalam keberbedaan.
Fungsi Budaya Perjumpaan dalam Interaksi Sosial: Menurunkan prasangka dan stereotip. Semakin sering orang bertemu dan berdialog, semakin kecil potensi salah paham. Memperkuat kohesi sosial
Perjumpaan menciptakan jaringan sosial antar komunitas yang memperkuat keutuhan masyarakat. Membangun resolusi konflik yang damai.
Dalam masyarakat majemuk, perjumpaan mencegah konflik dan menjadi basis solusi damai.
Menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan keadaban publik
Perjumpaan menjadi fondasi penting bagi identitas kolektif sebagai warga negara yang hidup bersama dalam perbedaan.
Contoh dalam Konteks Indonesia: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai ruang budaya perjumpaan lintas agama. Kegiatan “live-in” pemuda lintas agama, bakti sosial lintas komunitas. Diskusi lintas iman, seperti Interfaith Youth Camp atau Dialog Lintas Keyakinan. Tradisi gotong royong, yang meski berbeda agama, semua warga terlibat dalam kerja bersama.
Jadu, budaya perjumpaan adalah “jembatan sosial” yang dibangun atas kesediaan untuk mengenal, menghormati, dan hidup bersama dalam perbedaan. Dalam interaksi sosial, budaya ini.
Budaya perjumpaan yang kuat dan berkonstribusi bagi kerukunan dan harmoni bangsa.
Lemahnya budaya perjumpaan antarumat beragama di Indonesia akan berdampak terhadap kohesi sosial dan harmoni bangsa.
Di tengah masyarakat yang multikultural dan multireligius, perjumpaan antariman menjadi prasyarat penting bagi stabilitas dan perdamaian sosial.
Sayangnya, masih terdapat sekat-sekat sosial yang menghambat interaksi lintas agama. Melalui pendekatan sosiologis, perlu penelaahan faktor penyebab lemahnya budaya perjumpaan, dampak negatifnya bagi kehidupan berbangsa, serta rumusan strategi untuk menguatkan rekonsiliasi sosial berbasis nilai-nilai kebhinekaan.
Bangsa Indonesia dibangun di atas fondasi keragaman agama, etnis, dan budaya. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” menjadi landasan normatif penting dalam menjaga kesatuan nasional. Namun demikian, tantangan dalam merawat harmoni antarumat beragama terus hadir, terutama karena lemahnya budaya perjumpaan antarumat lintas agama. Budaya perjumpaan, yang dimaksud disini, adalah tradisi dialogis, interaksi sosial, dan kerja sama lintas iman yang membangun pemahaman serta kepercayaan antar kelompok keagamaan.
Ketiadaan ruang perjumpaan yang sehat dapat menyebabkan kesalahpahaman, polarisasi identitas, hingga munculnya konflik yang mengancam integrasi bangsa. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan mengurai akar persoalan lemahnya budaya perjumpaan dan dampaknya terhadap harmoni bangsa Indonesia.
Tinjauan Pustaka
1.Teori Interaksi Simbolik (Herbert Blumer)
Perjumpaan antarumat lintas agama tidak semata pertemuan fisik, tetapi sarat makna simbolik. Ketika interaksi jarang terjadi, stereotip lebih mudah berkembang, memperkuat prasangka negatif dan merusak relasi sosial.
2.Sosiologi Kerukunan Umat Beragama (Abdillah, 2001).
Kerukunan bersifat dinamis dan harus dipelihara secara aktif melalui komunikasi, saling pengertian, dan kerja sama dalam kesetaraan.
3.Pendekatan Multikulturalisme (Banks, 2009)
Masyarakat majemuk perlu mengembangkan pendidikan multikultural dan nilai-nilai pluralisme melalui sistem pendidikan dan kebijakan publik.
Metodologi
Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dan studi kasus. Sumber data diperoleh dari dokumen kebijakan FKUB, laporan konflik keagamaan, serta literatur ilmiah terkait kerukunan umat beragama dan multikulturalisme.
Pembahasan
A. Faktor Penyebab Lemahnya Budaya Perjumpaan
Sebab paling nyata afalah gegregasi sosial dan geografis. Komunitas agama tinggal di wilayah yang homogen, membatasi interaksi lintas iman mudah memicu timbulnya disharmoni bangsa.
Minimnya pendidikan multikultural dan moderasi beragama di Sekolah yang belum optimal dalam menanamkan toleransi dan nilai-nilai keberagaman adalah variabel yang mudahnya terjadi gesekan umat lintas agama.
Kuatnya Polarisasi Politik Identitas:
Politik elektoral sering mengeksploitasi isu agama, memperlebar jurang sosial.
Keterbatasan Ruang Dialog: Dialog antariman masih elitis dan tidak menjangkau akar rumput masyarakat.
Dominasi Pendekatan Keamanan: Penyelesaian konflik sering berbasis keamanan, bukan rekonsiliasi dan pemulihan relasi sosial.
Dampak terhadap Harmoni Bangsa.
Tumbuhnya Prasangka dan Intoleransi yang berakabutan kerentanan konflik horizontal.
Terganggunya Kohesi Sosial.
Erosi Solidaritas Warga Negara.
Tantangan terhadap Keutuhan Nasional.
Penguatan Budaya Perjumpaan
Revitalisasi Fungsi FKUB sebagai Mediator dan Fasilitator Dialog. FKUB perlu didukung anggaran, SDM, dan regulasi untuk mengarusutamakan ruang perjumpaan lintas iman secara berkelanjutan. Inisiasi Program Lintas Agama Berbasis Komunitas. Kegiatan seperti live-in, kerja bakti bersama, festival budaya lintas agama, dapat menciptakan hubungan sosial yang kuat.
Integrasi Pendidikan Toleransi dalam Kurikulum Nasional.
Pendidikan dasar hingga tinggi harus membangun kesadaran multikultural, inklusivitas, dan wawasan kebangsaan.
Pemanfaatan Media dan Teknologi untuk Promosi Harmoni. Narasi keberagaman, kisah sukses toleransi, dan ruang diskusi digital harus diperbanyak untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian.
Lemahnya budaya perjumpaan antarumat lintas agama merupakan akar dari rentannya harmoni sosial di Indonesia. Ketika interaksi antarumat beragama tidak terbangun dengan sehat dan berkelanjutan, maka mudah terjadi disintegrasi, prasangka, dan bahkan konflik. Oleh karena itu, membangun budaya perjumpaan bukan sekadar pilihan, melainkan strategi kunci dalam menjaga Indonesia sebagai bangsa yang damai, adil, dan bersatu dalam keberagaman.
Berikut penguatan dan konklusi ilmiah atas narasi “Budaya Perjumpaan Antarumat Lintas Agama dan Dampaknya terhadap Harmoni Bangsa” oleh Duski Samad, dalam perspektif sosiologis, kebijakan publik, dan pembangunan karakter kebangsaan:
Penguatan Gagasan
Budaya Perjumpaan sebagai Modal Sosial Bangsa Budaya perjumpaan bukan sekadar interaksi fisik, melainkan modal sosial yang memperkuat kepercayaan lintas kelompok (Putnam, 2000). Semakin sering perjumpaan terjadi, semakin dalam jalinan sosial yang terbentuk, dan semakin tinggi pula daya tahan masyarakat terhadap provokasi dan konflik.
Fungsi Strategis dalam Arsitektur Kerukunan Nasional Dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia, budaya perjumpaan menjadi salah satu pilar strategi nasional kerukunan umat beragama sebagaimana tercermin dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006. Budaya ini memperkuat pelibatan masyarakat akar rumput dalam merawat toleransi, jauh melampaui pendekatan birokratis dan elitis.
Menjawab Krisis Polarisasi Sosial dan Politik Di tengah polarisasi identitas yang tajam akibat politik elektoral berbasis agama dan media sosial yang menyuburkan disinformasi, budaya perjumpaan adalah antibodi sosial. Ia menumbuhkan empati, mempertemukan narasi, dan menciptakan ruang bersama untuk membangun bangsa di atas dasar pengakuan terhadap perbedaan.
Relevansi Teoritis dan Empiris Narasi ini mengukuhkan teori interaksi simbolik, bahwa makna sosial dibangun dalam proses interaksi. Ketidakterbukaan dan minimnya perjumpaan lintas iman menjadikan makna-makna sosial tentang “yang lain” dibentuk secara negatif melalui asumsi, bukan pengalaman nyata. Kajian empirik juga menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pengalaman lintas agama lebih toleran, lebih damai, dan lebih adaptif dalam konflik (Setara Institute, 2020).
Urgensi Rekontekstualisasi Peran FKUB FKUB, jika diberdayakan secara fungsional, dapat menjadi infrastruktur dialog horizontal yang menjembatani masyarakat lintas iman. Penguatan FKUB sebagai pelaksana diplomasi sosial berbasis keagamaan sangat relevan di era VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous), di mana kebijakan formal saja tak cukup mengikat batin masyarakat.
Kesimpulan:
Budaya perjumpaan adalah pondasi harmoni bangsa yang dibangun dari pengalaman hidup bersama, bukan sekadar wacana toleransi di atas kertas. Ketika budaya ini lemah—karena segregasi sosial, pendidikan yang eksklusif, dan pendekatan keamanan yang dominan—maka prasangka, ketegangan, bahkan kekerasan dapat tumbuh subur. Maka, memperkuat budaya perjumpaan adalah tindakan preventif strategis untuk menghindari disintegrasi dan menciptakan bangsa yang inklusif.
Rekomendasi Strategis:
Pengarusutamaan Perjumpaan Lintas Iman dalam Kebijakan Nasional dan Daerah
Melalui program lintas agama yang terstruktur dan berkelanjutan dalam RPJMN dan Perda Kerukunan.
Reformulasi Kurikulum Pendidikan Multikultural dan Moderasi Beragama
Pendidikan agama di semua level wajib menyertakan perspektif dialogis dan inklusif, bukan eksklusif dan apologetik.
Revitalisasi Peran FKUB dan Lembaga Adat dalam Rekonsiliasi Sosial
FKUB perlu difungsikan bukan hanya sebagai institusi izin, tetapi agen dialog, rekonsiliasi, dan edukasi publik.
Pemanfaatan Media Digital sebagai Ruang Perjumpaan Baru.
Kampanye narasi positif, kisah inspiratif toleransi, dan dialog digital harus diperbanyak untuk membendung arus ujaran kebencian.
Insentif dan Fasilitasi Kegiatan Budaya Perjumpaan
Pemerintah daerah dan pusat perlu mendukung program seperti interfaith camp, live-in, gotong royong lintas iman, melalui insentif, anggaran, dan pengakuan.
Penutup:
Membangun budaya perjumpaan adalah merawat jiwa Pancasila dan menghidupkan kembali semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam masyarakat yang kompleks dan beragam, perjumpaan adalah jembatan kemanusiaan, tempat perbedaan bertemu dalam keadaban, dan tempat perbedaan menjelma menjadi kekuatan persatuan.
DS.31072025.
Daftar Pustaka
• Abdillah, Masykuri. (2001). Demokrasi di Persimpangan Jalan: Respons Islam terhadap Pluralisme dan Toleransi di Indonesia. Jakarta: Paramadina.
• Banks, James A. (2009). Multicultural Education: Issues and Perspectives. Hoboken: Wiley.
• Blumer, Herbert. (1969). Symbolic Interactionism: Perspective and Method. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
• Komnas HAM. (2024). Laporan Tahunan Kerukunan dan Konflik Keagamaan di Indonesia.
• FKUB Nasional. (2023). Pedoman Strategis Kerukunan Umat Beragama.