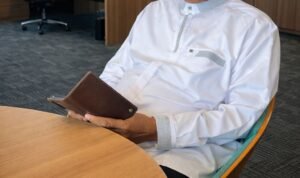SUMATERA BARAT BUKAN DAERAH INTOLERAN (3):
Minangkabau Kosmopolitan: Bukti Hidup Toleransi Budaya
Oleh: Duski Samad
Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat dan Guru Besar UIN Imam Bonjol
Tulisan ketiga ini ingin mengemukakan fakta ilmiah dan realitas hidup sosial masyarakat Minangkabau (baca Sumatera Barat) yang sejak awal terbentuknya dapat disebut kosmopolit dan berbudaya toleransi. Lebih dari itu topik ini diharapkan dapat menjadi bacaan alternatif bagi generasi milinial dan atau mereka yang tidak paham secara utuh tentang orang Minang, budaya Minang dan bukti hidup toleransinya orang Minangkabau. Tulisan ini Adalah bahagian dari ikhtiar untuk memastikan rukun, tolernasi dan harmoni Adalah budaya kite.
Narasi intoleransi yang kadang ditujukan kepada Sumatera Barat belakangan ini perlu diletakkan dalam konteks yang utuh, jujur, dan berpijak pada realitas sosial-budaya masyarakatnya. Masyarakat Minangkabau bukanlah komunitas yang eksklusif dan menutup diri terhadap yang berbeda. Sebaliknya, sejarah dan gaya hidup orang Minang mencerminkan kosmopolitanisme lokal — yaitu keterbukaan dan interaksi lintas budaya yang berlangsung secara alami dalam kehidupan sehari-hari.
Istilah “Minangkabau Kosmopolitan” yang dibuat di atas merujuk pada karakter masyarakat Minangkabau yang terbuka terhadap perbedaan budaya, agama, dan nilai, serta mampu menjalin hubungan lintas etnis dan global tanpa kehilangan identitasnya. Konsep ini bukan hanya menggambarkan mobilitas sosial dan geografi perantau Minang, tetapi juga mentalitas mereka yang adaptif dan toleran terhadap keragaman.
Makna dan dasar historis Minangkabau cosmopolitan paling nyata dapat dipahami dari akar filosofis. Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah menjadi pondasi hidup masyarakat Minangkabau. Ini mendorong keterbukaan sekaligus menjaga integritas agama dan budaya. Pepatah seperti “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” mencerminkan prinsip adaptasi lokal yang tidak menanggalkan identitas.
Sejarah merantau dan perantauan adalah nyata adanya, basuluah mato hari, ba galangang mato rang banyak. Tradisi merantau sejak masa lampau membuat orang Minangkabau terpapar berbagai budaya di Nusantara dan luar negeri. Kota-kota seperti Padang, Medan, Pekanbaru, Batam, Kuala Lumpur, Singapura, Eropah, hingga Mekkah menjadi simpul diaspora Minang yang plural.
Peran orang Minang dalam dunia pendidikan dan ekonomi banyak tokoh Minang berperan penting dalam pendirian sekolah modern, surat kabar, partai politik, dan pergerakan nasional. Eksistensi mereka dalam perdagangan dan ekonomi, termasuk dalam komunitas Tionghoa dan Arab, menunjukkan interaksi lintas budaya yang intens.
Kajian sosiologis dan antropologis dalam aspek multikulturalisme dalam praktik. Etnis Minang di kota-kota besar hidup berdampingan dengan Batak, Tionghoa, Melayu, Jawa, dan lainnya. Surau dan masjid menjadi ruang terbuka, bukan hanya untuk ibadah tapi juga mediasi sosial dan kultural. Bahasa dan Gaya Hidup. Bahasa Minang banyak menyerap kosakata Melayu, Arab, Belanda, dan Inggris. Pola konsumsi, pakaian, musik, dan kuliner (seperti rumah makan Padang) mencerminkan asimilasi dan difusi budaya.
Kerukunan dan relasi antar agama. Bukti konkret keberadaan gereja lebih dari satu abad di Kota Padang dan Bukittinggi tanpa kegaduhan berarti. Forum FKUB di Sumbar cukup aktif sebagai representasi nilai harmoni dalam relasi umat beragama.
Minangkabau Kosmopolitan bukan slogan kosong, tetapi identitas kolektif yang terbentuk dari sejarah panjang keterbukaan, perantauan, dan interaksi antarbudaya. Nilai-nilai ABS-SBK justru menjadi benteng etika dan spiritual dalam berinteraksi dengan dunia luar. Karena itu, tuduhan intoleransi terhadap Minangkabau harus dibaca secara hati-hati agar tidak mengabaikan fakta historis dan sosiologis yang mengakar kuat dalam realitas masyarakatnya.
BUKTI HIDUP TOLERANSI BUDAYA
Masyarakat Minangkabau memiliki sistem sosial matrilineal yang unik, yang turut mendorong kohesi sosial serta keterbukaan terhadap budaya lain (Navis, 1984). Proses migrasi yang dikenal sebagai “merantau” telah memperluas jaringan sosial Minangkabau, yang mengharuskan mereka beradaptasi dengan lingkungan baru tanpa kehilangan identitas budaya asli (Kato, 1982). Interaksi sosial yang intensif dengan masyarakat luar menciptakan pola pikir terbuka dan toleran terhadap perbedaan budaya.
Migrasi Minangkabau telah melahirkan bentuk-bentuk akulturasi budaya yang menarik. Interaksi Minangkabau dengan berbagai etnis di wilayah perantauan seperti Jawa, Kalimantan, hingga Malaysia menghasilkan identitas budaya baru yang tetap mempertahankan inti falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” (Amir, 2007). Menurut antropolog Koentjaraningrat (2005), kemampuan Minangkabau untuk melakukan adaptasi budaya sambil menjaga identitas asli mereka merupakan fenomena unik yang mencerminkan toleransi budaya dalam praktik nyata.
Kosmopolitanisme dalam budaya Minangkabau tercermin dalam tradisi kuliner, seni, bahasa, dan gaya hidup. Minangkabau tidak hanya mengadopsi budaya luar tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap budaya lokal tempat mereka menetap (Hadler, 2008). Misalnya, kuliner Padang menjadi makanan yang dikenal luas di berbagai wilayah Indonesia dan luar negeri, menunjukkan akseptasi yang tinggi dari masyarakat luar terhadap budaya Minang.
Dalam seni dan sastra, tokoh-tokoh Minangkabau seperti Hamka, Chairil Anwar, dan Taufiq Ismail merepresentasikan semangat kosmopolitanisme Minang yang mampu berdialog lintas budaya secara global (Azra, 2013). Bahasa Minangkabau sendiri telah dipengaruhi oleh berbagai unsur bahasa lain, menciptakan dialek yang fleksibel dan inklusif.
Fenomena kosmopolitanisme dalam budaya Minangkabau merupakan bukti nyata toleransi budaya yang hidup dan berkembang dalam dinamika global. Tradisi merantau telah menjadi katalis bagi masyarakat Minang untuk terbuka terhadap perbedaan budaya, menciptakan identitas kosmopolitan tanpa meninggalkan nilai-nilai asli mereka. Sebagai budaya kosmopolitan, Minangkabau memberikan kontribusi penting dalam upaya menciptakan keharmonisan sosial dan budaya di tengah keberagaman masyarakat modern.
Fakta dinamika sosial dan budaya Minang dapat terlihat jelas dalam pakaian dan kuliner populer di antaranya kain bugih dan lapek bugih. Kain Bugih, yang berasal dari etnis Melayu Bugis, merupakan kain yang sering dipakai dalam upacara adat Minang, khususnya oleh perempuan. Kehadirannya dalam busana tradisi Minang merupakan hasil dari akulturasi budaya Melayu dari pantai timur Sumatera dan Semenanjung Malaya dengan estetika lokal. Ini menunjukkan bahwa budaya Minangkabau bukan budaya “murni” yang tertutup, melainkan hasil dari pertukaran dan adopsi nilai-nilai dari luar yang diolah dengan prinsip “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
Fakta lain misalnya kata Cawan Pinggan. Keramik Cina dan Meja Hidang Minang. Cawan dan pinggan porselen asal Cina telah menjadi perlengkapan khas dalam rumah gadang dan acara kenduri Minang. Ini bukan hanya soal fungsi, tetapi simbol status sosial, selera estetik, dan relasi dagang-kultural antara Minangkabau dengan pedagang-pedagang dari Tiongkok sejak masa Kesultanan Pagaruyung.
Dalam baralek (perhelatan) dan batagak penghulu, cawan dan pinggan Cina menjadi pelengkap hidangan yang menyatukan tamu dari berbagai suku, agama, dan strata sosial. Ini menunjukkan adanya penghargaan terhadap produk budaya lain dalam ruang domestik dan ritual Minang.
Lebih dalam lagi dapat dibaca dari bahasa dan gaya hidup lintas budaya. Bahasa Minangkabau pun menyerap kosakata dari Arab, Melayu, Tionghoa, hingga Belanda dan Inggris. Dalam komunikasi harian, kata-kata seperti “mualaf”, “tokek”, “bule”, hingga “sayo” (sayur) membentuk jaringan linguistik kosmopolitan. Gaya hidup merantau orang Minang juga melatih masyarakatnya untuk terbuka, adaptif, dan bersahabat dengan budaya lain — dari Jakarta, Malaysia, hingga Eropa dan Amerika. Keberadaan rumah makan Padang yang tersebar di seluruh dunia menjadi bukti nyata ekspansi sosial-budaya yang damai, bukan agresif.
Minangkabau sebagai Model Toleransi Berbasis Budaya. Sumatera Barat, dengan fondasi adat dan syaraknya, bukan daerah intoleran. Tuduhan itu sering muncul karena fragmentasi informasi, kejadian insidental, dan bias persepsi yang tidak menggambarkan keseluruhan masyarakat. Relasi budaya seperti yang tergambar dalam Gunting Cino, Kain Bugih, dan Cawan Pinggan adalah bukti bahwa masyarakat Minangkabau hidup dalam harmoni dengan etnis, budaya, dan agama lain secara turun-temurun. Ini bukan toleransi yang dipaksakan, melainkan toleransi yang tumbuh dari interaksi, pengalaman sejarah, dan kearifan lokal.
Menguatkan Narasi Toleransi Berbasis Budaya dapat dilakukan lebih terencana dan terkelola dengab baik di antaranya melalui revitalisasi pendidikan budaya Minangkabau dalam kurikulum sekolah dan surau sebagai basis toleransi lokal. Pentingnya narasi publik berbasis budaya, untuk menanggapi tuduhan intoleransi dengan pendekatan sejarah dan fakta sosial. Pelibatan aktif etnis minoritas dalam kegiatan adat, budaya, dan keagamaan sebagai penguat kerukunan. Produksi karya budaya dan media (film, podcast, buku) yang menarasikan kosmopolitanisme Minang dari zaman ke zaman.
Kesimpulan: Minangkabau Kosmopolitan dan Bukti Hidup Toleransi Budaya
Tulisan ini menegaskan bahwa masyarakat Minangkabau, sejak masa awal pembentukannya, telah menunjukkan karakter kosmopolitan yang terbuka terhadap perbedaan budaya, agama, dan nilai-nilai lintas etnis tanpa kehilangan akar identitasnya. Falsafah hidup Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah menjadi kerangka nilai yang mendorong keterbukaan sekaligus menjaga integritas sosial-budaya.
Tradisi merantau, interaksi dagang lintas kawasan, serta kontribusi orang Minang dalam pendidikan, politik, dan ekonomi nasional menunjukkan bahwa keterlibatan mereka dalam jaringan sosial global adalah bentuk dari kosmopolitanisme yang hidup. Interaksi budaya yang tercermin dalam penggunaan Kain Bugih, Cawan Pinggan, maupun bahasa sehari-hari yang sarat pengaruh Arab, Tionghoa, Belanda, dan Melayu memperkuat klaim bahwa budaya Minang merupakan hasil sintesis dinamis dari pertukaran lintas budaya.
Fakta-fakta sosial dan antropologis membantah narasi negatif yang menuding Sumatera Barat sebagai daerah intoleran. Bukti kerukunan, seperti keberadaan gereja berusia lebih dari satu abad yang aman di Kota Padang dan Bukittinggi, serta aktifnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), menunjukkan bahwa harmoni antargolongan merupakan praktik yang tumbuh dari kearifan lokal, bukan sekadar slogan politik.
Lebih jauh, Minangkabau dapat dijadikan model toleransi berbasis budaya, karena nilai-nilainya tidak memaksakan keseragaman, melainkan menghidupkan keberagaman dalam semangat saling menghargai. Dalam konteks masyarakat global yang semakin terfragmentasi, narasi “Minangkabau Kosmopolitan” menjadi penting untuk disosialisasikan, terutama kepada generasi milenial dan publik luas yang belum memahami secara utuh warisan budaya Minangkabau.
Sebagai ikhtiar kolektif, perlu ada revitalisasi pendidikan budaya lokal di sekolah dan surau, pelibatan aktif etnis minoritas dalam kegiatan adat dan agama, serta produksi narasi publik melalui media budaya. Langkah-langkah ini tidak hanya menjaga harmoni, tetapi juga menjadikan Minangkabau sebagai contoh konkret bahwa toleransi dan keberagaman dapat tumbuh dari tradisi yang hidup, bukan dari regulasi yang kaku.
Dengan demikian, Minangkabau Kosmopolitan adalah identitas kultural yang otentik, bukan konstruksi artifisial, dan menjadi kontribusi penting bagi mozaik kebudayaan Indonesia yang rukun dan damai. DS.03082025.
Referensi
Amir, M. S. (2007). Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang. Jakarta: PT. Mizan Publika.
Azra, A. (2013). Renaisans Islam di Asia Tenggara: Sejarah Wacana & Kekuasaan. Bandung: Rosda.
Hadler, J. (2008). Muslims and Matriarchs: Cultural Resilience in Indonesia through Jihad and Colonialism. Ithaca: Cornell University Press.
Kato, T. (1982). Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
Kato, Tsuyoshi. Matriarchy and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia. Cornell University Press, 1982.
Koentjaraningrat. (2005). Pengantar Antropologi I. Jakarta: Rineka Cipta.
Lutz, J. (2006). “Minangkabau Ethnic Identity in Diaspora.” Asian Ethnicity, 7(1), 17–30.
Nasroen, M. (1957). Dasar Falsafah Adat Minangkabau. Jakarta: Balai Pustaka
Navis, A. A. (1984). Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Grafiti Pers.
Zainuddin, A. (2012). Sejarah Sosial Masyarakat Minangkabau. Padang: Pustaka Indonesia Press.