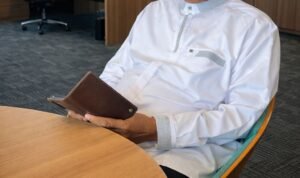SUMATERA BARAT BUKAN INTOLERAN (5)
Best Practice ada Nama Jalan dan Kampung Nias di Kota Padang dan Pariaman
Oleh: Duski Samad
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Barat
Tulisan kelima tentang Sumatera Barat bukan intoleran mengungkap pengalaman baik (best practices) adanya nama jalan dan nama daerah Kampung Nias di Kota Padang, di Kota Pariaman dan di Nagari Tanjung Basung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman di pesisir pantai Sumatera Barat. Kenyataan ini adalah fakta alam dan saksi hidup yang memastikan rukun, harmoni dan nyamannya kehidupan beragama di Sumatera Barat.
Migrasi dan Asal Usul Orang Nias (Ono Niha) mulai bermigrasi ke pesisir barat Sumatera, khususnya Padang dan Pariaman, sejak awal abad ke-20, terutama pada masa kolonial Belanda.
Sebagian besar dari mereka datang sebagai buruh pelabuhan, pekerja perkebunan, atau sebagai bagian dari relokasi sosial akibat faktor alam dan konflik lokal di Pulau Nias.
Menurut catatan kolonial, orang Nias sudah menjadi bagian dari penduduk Padang sejak 1905, terutama di kawasan pelabuhan Muara dan sekitarnya, dikenal sebagai Kampung Nias.
Kampung Nias di Kota Padang terletak di Kelurahan Kampung Pondok dan kawasan Muara, dekat pusat perdagangan zaman Belanda.
Komunitas Nias di sini hidup berdampingan dengan kelompok etnis lain seperti Minangkabau, Tionghoa, India Tamil, dan Jawa. Banyak dari mereka beragama Kristen Protestan dan Katolik, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu titik keragaman agama tertua di Padang.
Kampung Nias di Pariaman jumlah komunitas Nias di Pariaman lebih kecil jumlahnya dibanding Padang. Mereka umumnya bekerja di sektor informal dan pelabuhan, dan juga aktif dalam kegiatan keagamaan Kristen, khususnya di gereja-gereja kecil di pinggiran kota.
Interaksi Sosial dan Harmoni Antar Etnis
Model Integrasi Sosial komunitas Nias di Sumbar, khususnya di Padang dan Pariaman, adalah contoh integrasi minoritas secara damai dan produktif.
Mereka mengadopsi bahasa Minang sebagai alat komunikasi harian. Menghormati struktur adat lokal, meskipun tidak menjadi bagian dari sistem suku matrilineal Minangkabau. Aktif dalam kehidupan sosial—seperti gotong royong, pesta rakyat, dan kegiatan keagamaan lokal.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau mampu menerima komunitas luar selama mereka menjunjung nilai “tahu diri” dan menghormati tatanan sosial.
Simbiosis harmonis masyarakat Minang yang mayoritas Muslim dan masyarakat Nias yang Kristen hidup dalam prinsip toleransi fungsional. Konflik terbuka sangat jarang terjadi, bahkan saat ketegangan nasional menguat, kawasan Kampung Nias tetap stabil.
Dalam wawancara lapangan (Litbang Kemenag, 2018), warga Nias di Padang menyatakan: “Kami hidup aman di sini, tidak pernah dibeda-bedakan. Justru kami diberi kesempatan ikut kerja dan bergaul seperti biasa.”
Nilai Strategis dalam Wacana Kerukunan
Argumen historis Anti-Intoleransi.
Keberadaan Kampung Nias menjadi bukti sejarah bahwa masyarakat Sumatera Barat, khususnya Minangkabau, tidak memiliki tradisi diskriminatif terhadap kelompok berbeda agama atau etnis. Tuduhan intoleransi terhadap Sumbar termentahkan dengan kenyataan ini.
Model Relasi Minoritas-Majoritas. Komunitas Nias menunjukkan konsep minoritas yang tahu diri, menghormati aturan sosial, tidak memaksakan ekspresi keagamaan secara demonstratif.
Sementara komunitas Minang menerapkan peran mayoritas yang melindungi, tidak mengusir, tidak membatasi, dan membuka ruang hidup bagi yang berbeda. Ini selaras dengan filosofi “alam takambang jadi guru” — bahwa keragaman harus diterima sebagai bagian dari dinamika sosial yang natural.
Kampung Nias di Padang dan Pariaman adalah representasi sejarah multikulturalisme damai di pesisir barat Sumatera. Interaksi antara komunitas Nias yang Kristen dan mayoritas Minang Muslim menunjukkan harmoni sosial-keagamaan yang terkelola secara kultural, bukan hanya administratif. Kisah hidup bersama ini menjadi bukti nyata bahwa Sumatera Barat bukan daerah intoleran, tetapi memiliki warisan hidup toleransi yang kuat — jauh sebelum istilah pluralisme populer digunakan.
Kedatangan Etnis Nias ke Kota Padang.
Sejarawan mencatat bahwa komunitas Nias sudah hadir di Padang sejak abad ke-17, masuk melalui jalur perdagangan kolonial VOC dan EIC Inggris. Mereka tiba di Padang paling tidak sejak kontrak antara VOC dengan pemuka masyarakat Nias di Teluk Dalam pada tahun 1693 .
Dokumen VOC era akhir abad ke-17–awal abad ke-18 menyebutkan bahwa orang Nias sudah mendiami bandar niaga Padang sejak 1701.
Studi migrasi menjelaskan bahwa suku Nias secara sistematis dibawa oleh VOC pada abad ke-17 hingga abad ke-19 untuk bekerja sebagai pekerja kasar dan budak di Padang.
Meskipun dokumen spesifik untuk Pariaman tidak sebanyak Padang, migrasi orang Nias ke pesisir barat Sumatra—termasuk Pariaman—dimulai sejak abad ke-17, bersamaan dengan aktivitas pelabuhan di Padang, dan meluas ke kota-kota tetangga melalui perdagangan dan pekerjaan pelabuhan/perkebunan.
Komunitas Nias di Pariaman biasanya berasal dari migrasi lanjutan dari Padang atau dipekerjakan di sektor informal dan pelabuhan sepanjang pesisir barat Sumatra
Lokasi Periode Kedatangan Keterangan Utama
Kota Padang Abad ke-17 (paling lambat 1693 masehi diibawa VOC/EIC sebagai pekerja dan budak, mulai menetap sebagai komunitas awal di Padang . Lanjut ke abad ke-18/19 populasi berkembang, sebagian merdeka dan terlibat kegiatan ekonomi/pelabuhan.
Sedangkan di Kota Pariaman sekitar abad ke-17 ke atas migrasi paralel dari Padang sebagai pelabuhan dan perkebunan sepanjang pesisir barat Sumatra.
Hubungan dengan Keharmonisan Sosial.
Kehadiran orang Nias sejak abad ke-17–18, khususnya di wilayah Kampung Nias di Padang, mencerminkan bahwa masyarakat Minangkabau sudah mengakomodasi etnis dengan agama dan budaya berbeda secara damai sejak masa kolonial.
Adaptasi budaya yang signifikan, seperti penggunaan bahasa Minang dan pembentukan identitas adat baru (“Nias Padang”), menujukkan kemampuan berbaur yang tinggi tanpa menghilangkan identitas asli—ini menjadi modal sosial penting dalam membangun harmoni religi dan etnis.
NIAS PASCA REFORMASI
Realitas etnis Nias pasca era Reformasi (setelah 1998) di tiga lokasi utama: Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman (termasuk Tanjung Basung), dan Kota Pariaman—berserta hubungan mereka dengan dinamika sosial-keagamaan lokal pada umumnya terjaga sebagai mana sejak awal kedatangannya.
Kota Padang Kehadiran dan Integrasi.
Komunitas Nias di Kelurahan Seberang Palinggam adalah representasi minoritas Kristen yang telah diterima dalam struktur sosial. Dari survei tahun 2015, 7 dari 22 ketua Rukun Tetangga di sana adalah orang Nias‑Kristen—meskipun mayoritas warga beragama Islam—menandakan tingginya tingkat kepercayaan antar-etnis.
Model Hubungan Sosial: Malakok
Praktik malakok—yaitu model negosiasi identitas melalui adat lokal Minangkabau—dipraktikkan oleh komunitas Nias di Padang pasca Reformasi, menunjukkan sistem terbuka dan inklusif dalam struktur masyarakat Minang‑Muslim dan Nias‑Kristen .
Budaya dan Eksistensi
Tari Balanse Madam, warisan budaya Nias yang telah dibudayakan kembali oleh Sanggar Kutril sejak 2013, menjadi simbol integrasi budaya di masyarakat kota. Pelatihan seni ini turut membangun jembatan kultural antara warga Nias dan masyarakat luas Padang.
Kabupaten Padang Pariaman (Nagari Sungai Buluh Barat / Tanjung Basung II)
Sejarah Migrasi Pasca Reformasi. Etnis Nias mulai menetap di Korong Tanjung Basung II, Nagari Sungai Buluh Barat, sejak 1901 mengundang tujuh keluarga Nias oleh Datuak Kasupian dari Ketaping. Namun komunitasnya tumbuh secara signifikan antara tahun 1995–sekarang, khususnya setelah pembangunan infrastruktur membuka akses ekonomi lebih luas.
Komposisi Etnis-Agama dan Isu Konflik.
Pada 2020 data BPS menunjukkan 98 % penduduk nagari beragama Islam, sisanya komunitas minoritas seperti Nias sangat dihargai meski beragama Kristen/Katolik. Konflik horizontal sesekali terjadi, misalnya terkait peternakan babi antara 2001–2016, tetapi diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat tanpa eskalasi kekerasan luas.
Harmonisasi Sosial dan Moderasi
Sungai Buluh Barat dikenal sebagai “kampung moderasi beragama”, di mana dengan inisiatif lokal seperti FKUB, komunitas Minang-Muslim dan Nias-Kristen hidup dengan kohesi sosial melalui gotong royong dan ritual adat bersama, mencerminkan kohesi sosial yang kuat.
Kota Pariaman
Informasi spesifik tentang komunitas Nias pasca Reformasi di Kota Pariaman relatif terbatas. Namun migrasi Nias dari Padang ke Pariaman terjadi sejak periode kolonial dan terus berlanjut menjadi komunitas minoritas kecil di pesisir. Interaksi mereka cenderung sejalan dengan pola integrasi di Padang, walau tanpa catatan konflik signifikan.
Pasca Reformasi, komunitas etnis Nias di Padang dan Padang Pariaman berhasil mempertahankan eksistensi sosial‑kultural melalui asimilasi dan negosiasi identitas yang damai.
Praktik malakok di Padang dan pendekatan moderasi beragama di Tanjung Basung II menunjukkan bagaimana sistem adat Minang menjadi mekanisme efektif bagi integrasi minoritas. Meskipun minoritas tertentu menghadapi problem sosial seperti konflik sumber daya, penyelesaian berbasis adat dan edukasi sosial berhasil menjaga stabilitas.
Diplomasi kultural melalui seni, kepemimpinan lokal, dan moderasi agama telah memastikan etnis Nias tidak hanya eksis tetapi berharmoni dalam pluralitas Sumatera Barat.
ANALISIS SOSIOLOGIS
Analisis sosiologis dan politik mengapa etnis Nias akhir-akhir ini sesekali terlibat dalam gesekan sosial dengan masyarakat lingkungan, yang kerap membawa isu agama, meskipun secara historis mereka telah terintegrasi secara damai di Padang, Padang Pariaman, dan Pariaman.
1. Ketegangan Identitas dalam Ruang Sosial yang Padat dan Berbeda
Pluralitas dan Ketidakseimbangan Demografis.
Komunitas Nias, khususnya yang beragama Kristen/Katolik, hidup dalam lingkungan masyarakat mayoritas Muslim yang homogen secara kultural dan spiritual.
Ketidakseimbangan proporsi (misalnya di Nagari Sungai Buluh Barat, di mana 98% Muslim vs <2% Kristen) dapat memicu sensitivitas identitas ketika ada praktik atau ekspresi keyakinan yang dianggap berbeda, bahkan mengganggu oleh masyarakat lokal.
Dalam teori konflik Horowitz, “the ethnic proximity paradox” menjelaskan bahwa semakin dekat dua kelompok hidup berdampingan secara fisik tetapi berbeda identitas, semakin tinggi potensi gesekan jika tidak dikelola secara aktif.
2.Gesekan Berbasis Gaya Hidup dan Praktik Keagamaan
Isu Ternak Babi dan Pola Konsumsi.
Kasus peternakan babi oleh warga Nias di Tanjung Basung II (2001–2016) menjadi contoh klasik konflik berbasis nilai-nilai agama dan gaya hidup. Masyarakat Muslim menganggap keberadaan babi sebagai najis, sementara bagi warga Nias (Kristen), babi adalah bagian dari tradisi konsumsi dan ekonomi rumah tangga.
Konflik muncul bukan karena kebencian agama, tetapi karena tumpang tindih ruang hidup dan simbol keagamaan yang tidak dikomunikasikan secara baik.
3.Politik Identitas dan Stigmatisasi Pascakonflik Nasional.
Pascainsiden Lokal dan Provokasi Digital. Pasca Reformasi, Indonesia mengalami peningkatan polarisasi identitas, khususnya setelah konflik bernuansa agama seperti Poso, Ambon, dan insiden Ahok. Dalam konteks ini, isu kecil di level lokal dapat “meledak” jika dikaitkan dengan narasi nasional.
Media sosial mempermudah penyebaran opini yang menyulut prasangka antaragama. Misalnya: Suara adzan dianggap terganggu oleh aktivitas gereja, ritual Natal dianggap “provokatif” karena pengeras suara, Pembangunan tempat ibadah minoritas tanpa sosialisasi dianggap “diam-diam dan melanggar norma.”
Dalam analisis sosiologi digital, ini disebut efek “amplifikasi simbolik” — di mana simbol minoritas diperbesar persepsinya sebagai ancaman terhadap dominasi kultural mayoritas.
4.Lemahnya Kapasitas Mediasi Formal dan Kultural.
Menurunnya Peran Ninik Mamak dan Lembaga Adat.
Praktik malakok dan musyawarah adat terbukti efektif sejak zaman kolonial dalam meredam gesekan, namun pasca Reformasi, otonomi daerah tidak selalu diikuti dengan revitalisasi lembaga adat.
Banyak konflik tidak lagi diselesaikan lewat kerapatan adat, tetapi masuk ke media sosial atau ruang hukum formal tanpa pendekatan dialogis. Padahal, nilai adat Minangkabau—kok gadang indak manggaduah, kok ketek indak mancarih— adalah kunci menjaga harmoni antaretnis.
5.Kesenjangan Sosial dan Ketegangan Ekonomi.
Etnis Nias banyak yang bekerja di sektor informal dan padat karya: buruh, pedagang kaki lima, peternak kecil.
Ketika terjadi ketegangan ekonomi seperti pandemi atau krisis pangan, minoritas etnis lebih mudah menjadi kambing hitam atau dianggap tidak berkontribusi terhadap “kebersamaan” lokal. Teori Scapegoating (Allport, 1954) menyebut bahwa kelompok minoritas lebih rentan disalahkan atas masalah sosial, meski tidak terkait langsung.
Akar Konflik dan Rekomendasi Strategis
Akar Konflik:
Bukan semata-mata soal agama, tetapi soal pengelolaan ruang hidup bersama, kesenjangan identitas, dan kurangnya komunikasi antarbudaya.
Ketegangan muncul ketika ekspresi agama atau budaya dipersepsi sebagai ancaman terhadap nilai dominan, meski secara niat tidak bermaksud demikian.
Rekomendasi:
Revitalisasi Lembaga Adat dan FKUB Nagari: Sistem musyawarah dan negosiasi identitas seperti malakok perlu dikembalikan sebagai kanal mediasi utama.
Pendidikan Multikultural Berbasis Lokal: Sekolah-sekolah dan tokoh agama perlu menyisipkan kurikulum toleransi yang kontekstual dengan realitas lokal seperti di Tanjung Basung.
Penguatan Etika Sosial Minoritas: Komunitas Nias perlu terus mengembangkan sikap tahu diri, dengan tetap menjaga hak asasi tanpa konfrontasi terbuka, sebagaimana prinsip minoritas hidup damai dalam sistem Minangkabau.
Pengawasan Narasi Publik di Media Sosial: Pemerintah dan tokoh masyarakat perlu aktif menyikapi narasi provokatif agar tidak menyulut stigma kolektif.
Isu gesekan yang melibatkan etnis Nias akhir-akhir ini harus dibaca bukan sebagai bukti kegagalan integrasi, melainkan sebagai tantangan baru dalam merawat harmoni di era keterbukaan informasi dan pergeseran nilai sosial. Kuncinya adalah memperkuat kembali “local wisdom” sebagai mekanisme resolusi yang hidup dan mengakar di masyarakat Minangkabau.
KONKLUSI
Sumatera Barat bukan daerah intoleran, dan keberadaan Kampung Nias di berbagai wilayah menjadi bukti sejarah sekaligus aktual bahwa harmoni antaretnis dan antaragama telah tumbuh dan terawat secara alami dalam kultur Minangkabau.
Keberadaan etnis Nias yang mayoritas Kristen/Katolik di tengah mayoritas masyarakat Minang yang Muslim, sejak abad ke-17 hingga kini, menunjukkan bahwa Sumatera Barat memiliki tradisi sosial inklusif dan toleran yang sudah teruji oleh waktu dan peristiwa sejarah.
Kampung Nias di Kota Padang, Kota Pariaman, dan Tanjung Basung Padang Pariaman tidak hanya menjadi jejak geografis migrasi, tapi juga jejak budaya multikultural yang menunjukkan betapa masyarakat Minangkabau mampu mengakomodasi perbedaan tanpa kehilangan identitasnya sendiri.
Model relasi seperti: tahu diri dari komunitas minoritas (etnis Nias), dan melindungi dengan bijak dari kelompok mayoritas (Minangkabau), adalah cerminan keseimbangan sosial berbasis nilai adat dan agama, sebagaimana tertuang dalam falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Meski dalam beberapa tahun terakhir terjadi gesekan horizontal yang melibatkan isu agama, realitas tersebut tidak cukup kuat untuk mengaburkan fakta dasar: bahwa kerukunan di Sumbar adalah norma, dan konflik adalah anomali.
Ketegangan yang muncul lebih disebabkan oleh: kesenjangan demografis, perbedaan gaya hidup dan simbol keagamaan, minimnya kanal komunikasi budaya, serta provokasi melalui media sosial, dari pada karena adanya kebencian ideologis antarumat.
Oleh karena itu, revitalisasi nilai lokal, seperti: musyawarah nagari, praktik malakok, dan kurikulum toleransi berbasis kearifan lokal, harus menjadi arus utama strategi peredam konflik dan penguat harmoni.
Kampung Nias adalah bukan hanya tempat, tapi simbol. Simbol bahwa pluralisme bukan konsep asing bagi Sumatera Barat, tapi warisan hidup dari sejarah panjang kebersamaan Minang dan Nias.
Maka dari itu, Sumatera Barat bukan hanya tidak intoleran—tetapi justru layak menjadi model nasional bagi pengelolaan keragaman yang berbasis pada akar budaya, agama, dan kearifan lokal yang hidup.Ini bukan narasi defensif, tapi fakta yang perlu dirawat, ditegaskan, dan diwariskan. DS>04082025