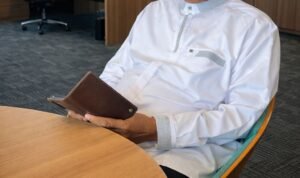PARADOKS MORAL DAN AGAMA
Oleh: Duski Samad
Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang
Paradok moral muncul ketika penulis menyaksikan di televisi tersangka korupsi, OTT, Noel wamennaker berbaju oranye berwajah senyum, menunjukkan simbol agama, seolah-olehnya ia tidak bersalah atau tak berdosa saja.
Paradoks moral adalah suatu keadaan atau persoalan ketika nilai, norma, atau prinsip moral yang sama-sama dianggap benar justru bertentangan satu sama lain sehingga sulit menentukan mana yang harus diprioritaskan.
Contoh sederhana dalam etika, ada prinsip “jangan berbohong” dan ada juga prinsip “selamatkan nyawa manusia”. Jika seorang pembunuh menanyakan di mana seseorang bersembunyi, apakah kita harus jujur (tidak berbohong) ataukah berbohong demi menyelamatkan nyawa?
Inilah yang disebut paradoks moral, karena dua kewajiban moral sama-sama kuat, tetapi tidak bisa dipenuhi sekaligus.
Paradoks moral cirinya benturan nilai ada dua (atau lebih) prinsip etis yang berbenturan. Tidak ada solusi mudah pilihan apapun akan mengorbankan satu nilai moral.
Menghadirkan dilema menuntut penalaran lebih dalam, sering kali juga melibatkan pertimbangan konteks sosial, agama, hukum, dan hati nurani.
Dalam Islam
Paradoks moral kadang diperdebatkan dalam usul fiqh dan tasawuf. Misalnya: Prinsip menjaga agama versus menjaga jiwa dalam maqashid syariah.
Dalam kondisi darurat (dharurah), yang biasanya haram bisa menjadi boleh (misalnya makan bangkai untuk menyelamatkan nyawa).
Paradoks moral bukan berarti tidak ada kebenaran, melainkan ujian untuk menimbang mana maslahat yang lebih besar dan mafsadat yang lebih kecil.
PARADOKS MORAL DALAM POLITIK
1. Kekuasaan untuk Melayani vs Kekuasaan untuk Memperkaya. Moral ideal: Politik adalah amanah untuk melayani rakyat (amanah dan maslahat).
Realitas: Banyak pejabat justru menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi/kelompok.
Paradoks: Rakyat menginginkan pemimpin yang jujur dan amanah, tetapi sistem politik yang transaksional sering “memaksa” kompromi moral.
2. Demokrasi vs Politik Uang
Moral ideal: Demokrasi seharusnya berjalan dengan suara rakyat yang bebas.
Realitas: Banyak kontestasi politik tercemar money politics (serangan fajar, sogokan).
Paradoks: Politisi butuh suara menggunakan uang. Pemilih butuh uang cepat menerima. Akhirnya demokrasi jadi “pasar transaksional” bukan moralitas.
3. Pluralisme vs Politik Identitas
Moral ideal: Indonesia adalah negara Pancasila yang merangkul perbedaan.
Realitas: Politik identitas (agama, etnis, daerah) sering dipakai demi mobilisasi suara.
Paradoks: Slogan persatuan digaungkan, tetapi praktiknya politisasi perbedaan justru memperlebar jurang intoleransi.
4. Janji Politik vs Realisasi
Moral ideal: Janji adalah amanah, wajib ditepati (QS. Al-Isra: 34).
Realitas: Banyak janji kampanye tidak terealisasi karena alasan “dinamika politik”.
Paradoks: Rakyat percaya dengan janji untuk memilih, tapi sering kecewa ketika janji hanya menjadi alat perebutan suara.
5. Kedaulatan Rakyat vs Kepentingan Elite
Moral ideal: “Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.”
Realitas: Kebijakan sering lebih menguntungkan elite politik dan oligarki ekonomi.
Paradoks: Rakyat yang seharusnya berdaulat malah menjadi objek politik, bukan subjek.
6. Etika Politik vs Survival Politik
Moral ideal: Politik berlandaskan etika (adil, amanah, jujur).
Realitas: Untuk bertahan, politisi sering melakukan kompromi, koalisi aneh, bahkan loncat partai.
Paradoks: Etika dikorbankan demi kelangsungan hidup politik pribadi.
Paradoks moral dalam politik Indonesia muncul karena ketegangan antara nilai luhur (amanah, keadilan, pengabdian) dengan praktik pragmatis (uang, kekuasaan, kepentingan kelompok).
Dalam kacamata Islam dan ABS-SBK, politik seharusnya adalah jalan ibadah dan kemaslahatan, bukan hanya perebutan kursi. Maka dibutuhkan:
Pendidikan politik berakhlak, Teladan pemimpin bermoral,
Penguatan regulasi antikorupsi dan anti money politics.
PEJABAT BERCITRA ALIM
Tingkah polah pejabat selalu terus semangkin sulit dimengerti, khususnya dalam mencitra diri alim, taat dan seperti peduli pada agama. Padahal nyata-nyata pecundang, masih saja bawa atribut agama saat berbaju oranye.
Fenomena ini bukan sekadar tren, tetapi memiliki akar yang dalam pada struktur sosial dan politik Indonesia dan prilaku pejabat yang untuk mendapatkan amanah melalui transaksi, termasuk jual beli agama.
1. Kajian nash
Secara teologis, Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia, menekankan pentingnya integritas moral dan kepemimpinan yang adil. Banyak ayat dalam Al-Qur’an dan hadis yang menegaskan hal ini. Surah An-Nisa’ (4:58), “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil…” menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan keadilan.
Pejabat yang menampilkan diri religius secara ideal seharusnya mencerminkan nilai-nilai ini, bukan sekadar simbol.
Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah seorang hamba diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyat, kemudian ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga atasnya.” (HR. Muslim).
Hadis ini memberikan peringatan keras bahwa kepemimpinan yang tidak jujur dan menipu rakyat akan berkonsekuensi besar di akhirat.
Penggunaan simbol agama oleh pejabat seharusnya menjadi pengingat akan tanggung jawab ini, bukan alat untuk menutupi ketidakjujuran.
2. Kajian Ilmiah
Studi ilmiah tentang hubungan agama dan politik di Indonesia telah lama menjadi fokus para akademisi. Mereka melihat fenomena ini dari berbagai sudut pandang sosiologis, politik, dan antropologis.
Politik Identitas: Para ahli seperti Sumanto Al Qurtuby dan peneliti lainnya melihat fenomena ini sebagai bagian dari politik identitas, di mana identitas agama digunakan sebagai alat politik untuk mobilisasi massa dan meraih kekuasaan. Ini bukan hal baru, tetapi semakin menguat di era demokrasi pasca-Reformasi.
Komodifikasi Agama: Konsep komodifikasi agama (kompas.com) juga relevan, di mana agama dijadikan komoditas politik yang diperdagangkan untuk mendapatkan dukungan.
Pejabat menampilkan citra religius sebagai “produk” yang menarik bagi mayoritas pemilih.
Dampak Polarisasi: Penelitian menunjukkan bahwa politisasi agama dapat menimbulkan polarisasi dan ketidakstabilan sosial. Contoh nyata terlihat dalam beberapa kasus Pilkada dan Pemilu Presiden, di mana isu-isu keagamaan memecah belah masyarakat dan menciptakan ketegangan.
Paradoks Moralitas: Studi lain, seperti yang dikemukakan oleh Kompas, menyoroti paradoks moralitas. Pejabat yang terlihat saleh dan sering berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan ternyata juga banyak yang terlibat dalam kasus korupsi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara simbol agama yang ditampilkan dengan perilaku etis yang sesungguhnya.
3. Politik Indonesia Kontemporer
Dalam praktik politik saat ini, fenomena ini terlihat dalam berbagai aspek:
Salam Lintas Agama: Penggunaan salam lintas agama di pidato-pidato pejabat menjadi hal yang umum. Meskipun tujuannya adalah untuk menunjukkan toleransi dan inklusivitas, bagi sebagian pihak, ini juga dilihat sebagai bagian dari strategi politik untuk merangkul semua kelompok agama.
Peran Ulama dan Pemuka Agama: Pemuka agama seringkali dilibatkan dalam kampanye politik. Ijtima Ulama dan dukungan dari tokoh-tokoh agama menjadi faktor penting dalam menentukan kemenangan seorang calon.
Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi religius sering dianggap sama pentingnya dengan legitimasi politik.
Narasi “Pemimpin yang Agamis”: Sejak era Orde Baru hingga saat ini, citra presiden atau kepala daerah sebagai sosok yang religius dan dekat dengan rakyat melalui kegiatan keagamaan (seperti salat Jumat, kunjungan ke pesantren, atau haji) terus menjadi bagian dari strategi komunikasi politik. Ini menciptakan narasi bahwa seorang pemimpin yang baik haruslah “agamis” dan bermoral.
Secara keseluruhan, penguatan narasi di atas menunjukkan bahwa fenomena pejabat yang menampilkan diri religius di Indonesia adalah isu yang kompleks. Meskipun secara ideal harus berakar pada integritas moral, dalam realitas politik kontemporer, seringkali menjadi alat strategis yang bisa memicu baik dampak positif maupun negatif.
Kesimpulan
Paradoks moral dalam politik Indonesia tampak nyata ketika pejabat yang terjerat kasus korupsi tetap menghadirkan citra religius—berwajah senyum, melambaikan simbol agama, bahkan berbaju oranye KPK seolah tanpa rasa bersalah. Fenomena ini menyingkap jurang antara simbol kesalehan dan perilaku politik yang sesungguhnya.
Secara teologis, Islam menuntut kepemimpinan yang amanah, adil, dan jujur sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an (QS. An-Nisa: 58) dan hadis Nabi SAW tentang pemimpin yang menipu rakyatnya. Namun dalam realitas politik, agama sering dijadikan komoditas identitas untuk meraih legitimasi, bukan sebagai sumber moralitas. Inilah paradoks moral, benturan antara nilai luhur agama dan praktik kekuasaan yang pragmatis.
Dalam politik kontemporer Indonesia, paradoks ini hadir dalam bentuk:
Kekuasaan untuk melayani vs memperkaya diri
Demokrasi ideal vs politik uang
Pluralisme Pancasila vs politik identitas
Janji kampanye vs realisasi
Kedaulatan rakyat vs kepentingan elite
Etika politik vs survival politik
Akibatnya, politik kehilangan martabat sebagai jalan ibadah dan kemaslahatan, bergeser menjadi arena transaksi kepentingan. Simbol agama dipakai sebagai ornamen citra, tetapi abai pada substansi moral.
Karena itu, jalan keluar dari paradoks moral ini adalah:
Menghidupkan pendidikan politik berakhlak,
Menegakkan teladan pemimpin yang bermoral,
Menguatkan regulasi anti-korupsi dan anti politik uang,
Mengembalikan agama pada ruhnya: sumber etika publik, bukan alat citra politik.
Politik Indonesia hanya akan menemukan marwahnya bila agama benar-benar menjadi nilai penggerak integritas, bukan sekadar atribut pencitraan kekuasaan. Ds.27082025